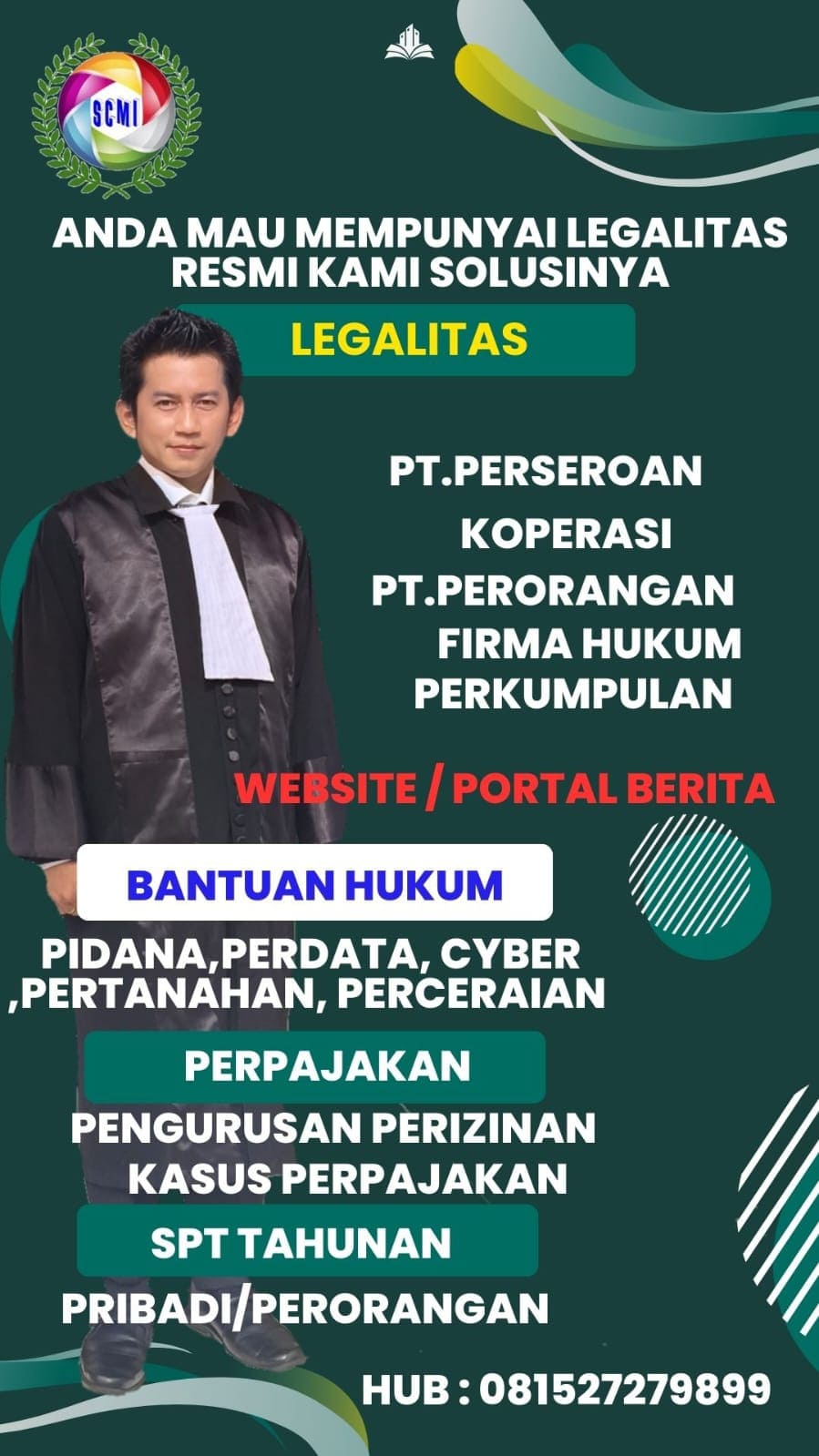Pekanbaru – Seputar indonesia.co.id – Advokat Padil Saputra & Partners atas nama Jekson Jumari Pandapotan Sihombing, alias Jekson Sihombing, mengirimkan dokumen hak jawab terhadap pemberitaan Haluanriau.co kepada redaksi media ini, Minggu, 08 Februari 2026. Dokumen tersebut secara telak membeberkan fakta penting tentang borok busuk bagaimana hukum dijalankan di Indonesia, khususnya oleh Kapolda Riau Herry Heryawan, yang berselingkuh dengan perusahaan perusak hutan Riau, Surya Dumai Group.
Dokumen hak jawab tersebut menegaskan bahwa status P-21, yang adalah kelengkapan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak otomatis meniadakan dugaan kriminalisasi, pelanggaran prosedur, maupun rekayasa hukum. Seperti ditegaskan Wilson Lalengke, seorang aktivis HAM internasional Indonesia yang mengatakan bahwa kelengkapan administrasi bukanlah bukti keadilan, karena berpotensi dibuat sesuka hati oleh para pejabat yang tidak berintegritas.
“Administrasi bukanlah bukti keadilan. Negara yang puas dengan stempel birokrasi, sementara rakyat dirampas haknya, sedang mengkhianati kontrak sosial dan kontrak moral dengan rakyat,” kata lulusan pasca sarjana bidang _Global Ethics_ dari _Birmingham University, England_, ini, Minggu, (8/2/2026).
Setidaknya terdapat dua kasus kriminalisasi yang dapat dijadikan argumentasi hukum dalam membedah pernyataan Kapolda Riau Herry Heryawan yang disampaikan melalui Kabid Humas Riau soal P-21 Jekson Sihombing beberapa hari lalu. Pertama, perkara kriminalisasi Haris Azhar oleh Luhut Binsar Panjaitan di PN Jakarta Pusat yang meski Kejaksaan menerbitkan P-21, pengadilan memutus bebas karena unsur pidana tidak terbukti.
Kedua, perkara mahasiswa Unversitas Riau Khariq Anhar, korban kriminalisasi aparat polisi, di PN Jakarta Pusat yang diputus bebas pada 23 Januari 2026 lalu. Meski telah dinyatakan P-21, pengadilan membebaskan terdakwa karena cacat prosedural, yakni alat bukti tidak memenuhi standar pembuktian; terdapat persoalan serius dalam proses penegakan hukum sejak tahap awal; dan penafsiran unsur pidana tidak dapat dipaksakan atau bersifat sumir.
Berdasarkan dua penetapan hakim PN Jakarta Pusat yang dapat dijadikan jurispudensi itu, sangat jelas bahwa pernyataan Kapolda Riau Herry Heryawan yang mengatakan terbitnya status P-21 menandakan tindakan penangkapan Jekson Sihombing bukanlah kriminalisasi, tidak berdasar sama sekali. Penting juga digarisbawahi bahwa cacat prosedural di tahap penyelidikan dan penangkapan tetap dapat berujung pada pembebasan terdakwa, meskipun berkas dinyatakan lengkap atau P-21; dan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada formalitas administrasi, melainkan harus diuji secara substansial di hadapan hakim yang independen.
Dengan demikian, menjadikan status P-21 sebagai dalih untuk menepis dugaan kriminalisasi, penjebakan, atau pelanggaran prosedur adalah argumentasi yang menyesatkan dan tidak berdasar secara hukum. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa P-21 tidak berarti adanya kesalahan terdakwa, juga bukan bukti bahwa Kapolda Riau Herry Heryawan tidak melakukan kriminalisasi terhadap Jekson Sihombing. Pengadilan Negeri Pekanbaru tetap berhak dan wajib menilai keabsahan penangkapan dan proses hukum.
*Kriminalisasi yang Tidak Dibantah*
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak PT. Ciliandra Perkasa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan PN Pekanbaru mengungkap fakta yang justru mengkonfirmasi adanya kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan anti korupsi Jekson Sihombing oleh pihak pelapor sendiri. Keterangan di bawah sumpah pihak pelapor, Basril Boy, yang merupakan Legal Corporate PT. Ciliandra Perkasa, mengungkap tiga fakta krusial. Pertama, adanya koordinasi pihak pelapor dengan Polda Riau sejak pagi (±09.00 WIB), delapan jam sebelum pertemuan dengan Jekson sebagai target kriminalisasi.
Kedua, rekan pelapor dari perusahaan yang sama, Nur Riyanto, telah menyiapkan uang Rp. 150 juta, yang menunjukkan adanya pengondisian atau perencanaan untuk terjadinya tindak pidana pemerasan yang dituduhkan kepada Jekson. Ketiga, proses penangkapan terjadi pukul 17.20–17.33 WIB, sementara laporan polisi baru dibuat pukul 21.36 WIB.
Fakta ini menunjukkan adanya _reverse procedure_: penangkapan mendahului laporan polisi. Dalam hukum acara pidana, hal ini adalah pelanggaran serius. KUHAP menegaskan bahwa laporan polisi (LP model B) adalah dasar formil dimulainya proses hukum, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan (LP model A). Namun dalam kasus ini, penangkapan dilakukan ±4 jam sebelum laporan dibuat. Laporan polisi justru menyusul untuk membenarkan tindakan yang sudah terjadi.
“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pelecehan terhadap prinsip _due process of law_. Aparat menjadikan hukum sebagai alat pembenaran belaka, bukan pedoman melaksanakan tugas penegakan hukum,” jelas Wilson Lalengke.
*Klaim Sesat OTT*
Padil Saputra juga dengan tegas menolak klaim Kapolda Riau Herry Heryawan bahwa Jekson Sihombing ditangkap dalam operasi tertangkap tangan (OTT). Pertama, peristiwa tidak spontan, melainkan hasil pengondisian (koordinasi polisi, uang disiapkan, lokasi diarahkan) alias Kapolda Riau bersama anggotanya mempersiapkan sebuah skenario terjadinya tindak pidana atau dalam bahasa sederhana sebagai rekayasa peristiwa pidana.
Kedua, tidak ada ancaman langsung dari Jekson Sihombing saat penyerahan uang, dan berdasarkan rekaman CCTV tempat kejadian, Jekson justru menolak menerima tas merah marun yang katanya berisi uang. Ketiga, adanya ketidakpastian waktu penangkapan, apakah pada pukul 17.20 atau 17.33 WIB yang merupakan perbedaan waktu cukup jauh, yang membuka ruang rekayasa kronologi.
Dalam perspektif Immanuel Kant (1724-1804), tindakan aparat semacam ini melanggar imperatif kategoris yang mewajibkan setiap orang bertindak berdasarkan prinsip atau aturan yang dapat diuniversalkan menjadi hukum umum, serta selalu memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sekadar alat. Jika Kapolda Riau Herry Heryawan dan jajarannya mengondisikan terjadinya sebuah kejahatan, maka hukum kehilangan moralitasnya.
Saksi M. Riki dan Andika Adi Putra, keduanya polisi dari Tim RAGA Polda Riau, saat bersaksi di bawah sumpah di PN Pekanbaru, mengakui bahwa penangkapan dilakukan tanpa mengecek laporan polisi dan tanpa surat perintah. Penangkapan Jekson Sihombing hanya berdasarkan perintah pimpinan alias Kapolda Riau Herry Heryawan. Pernyataan ini adalah pengakuan eksplisit bahwa prosedur KUHAP diabaikan.
Filsuf Yunani kuno, Plato (428–347 SM) dalam _The Republic_ mengingatkan bahwa ketika hukum tunduk pada kehendak penguasa, maka negara jatuh ke dalam bentuk tirani. Apa yang dilakukan oleh Kapolda Riau Herry Heryawan dan gerombolannya adalah cermin dari peringatan Plato: hukum dijadikan alat kekuasaan, bukan penjaga keadilan.
Rangkaian peristiwa kriminalisasi menunjukkan adanya pola penjebakan atau _entrapment_. Aparat Polda Riau dan pelapor Basril Boy dari perusahaan perusak hutan PT. Ciliandra Perkasa merencanakan terjadinya peristiwa pidana dengan modus pemerasan yang tujuan utamanya menangkap aktivis lingkungan Jekson Sihombing. Dalam doktrin hukum pidana, aparat dilarang menciptakan kejahatan. Jika kejahatan lahir dari skenario, maka asas legalitas hancur.
Wilson Lalengke menggambarkan tindakan Kapolda Riau Herry Heryawan yang melakukan penjebakan terhadap warga sebagai kriminalisasi paling brutal dan keji. “Penjebakan adalah bentuk kriminalisasi yang paling keji di dunia. Negara tidak lagi menindak kejahatan, melainkan menciptakannya. Ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang biasa disebut sebagai bentuk tindak kejahatan negara _(state crime),_” tuturnya.
*Konsekuensi Yuridis*
Karena penangkapan Jekson oleh Kapolda Riau Herry Heryawan dilakukan tanpa dasar hukum, maka seluruh proses hukum lanjutannya ikut tercemar sebagai proses kriminalisasi oleh JPU dan majelis hakim. Dalam hukum dikenal doktrin _fruit of the poisonous tree,_ yakni bukti yang lahir dari pelanggaran prosedural tidak sah dan harus dikesampingkan.
John Locke (1632-1794) dalam _Two Treatises of Government_ menulis bahwa kekuasaan negara hanya sah jika dijalankan berdasarkan hukum yang adil. Jika Kapolda Riau Herry Heryawan mengarahkan anggotanya sebagai aparat negara menciptakan kejahatan bersama geng gelapnya Surya Dumai Group (PT. Ciliandra Perkasa), maka negara telah melanggar kontrak sosial dan kehilangan legitimasi.
Hak jawab yang disampaikan PH Jekson Sihombing, Advokat Padil Saputra & Partner, yang dikirimkan ke ratusan media se-tanah air melalui jaringan PPWI ini bukan sekadar bantahan terhadap pemberitaan, melainkan peringatan keras bahwa hukum di Indonesia masih rentan dijadikan alat kekuasaan. Status P-21 tidak boleh menutup mata atas cacat prosedural, dugaan penjebakan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara keji oleh Kapolda Riau Herry Heryawan dan aparat polisi di Polda Riau.
Sebagaimana ditegaskan oleh Wilson Lalengke dan para filsuf besar, hukum tanpa keadilan adalah tirani, kekuasaan tanpa kontrol hukum. Oleh karena itu, kejaksaan dan pengadilan harus berani menegakkan prinsip _due process of law_ (proses hukum yang adil), membebaskan terdakwa jika prosedur dilanggar, dan mengembalikan martabat hukum sebagai pelindung rakyat. JPU dan Majelis Hakim jangan terseret ikut arus Polda Riau menjadi alat pengusaha bejat Surya Dumai Group dan atau terintervensi oleh legitnya uang haram perusahaan pelaku penggelapan triliunan uang negara tersebut.
(Red)